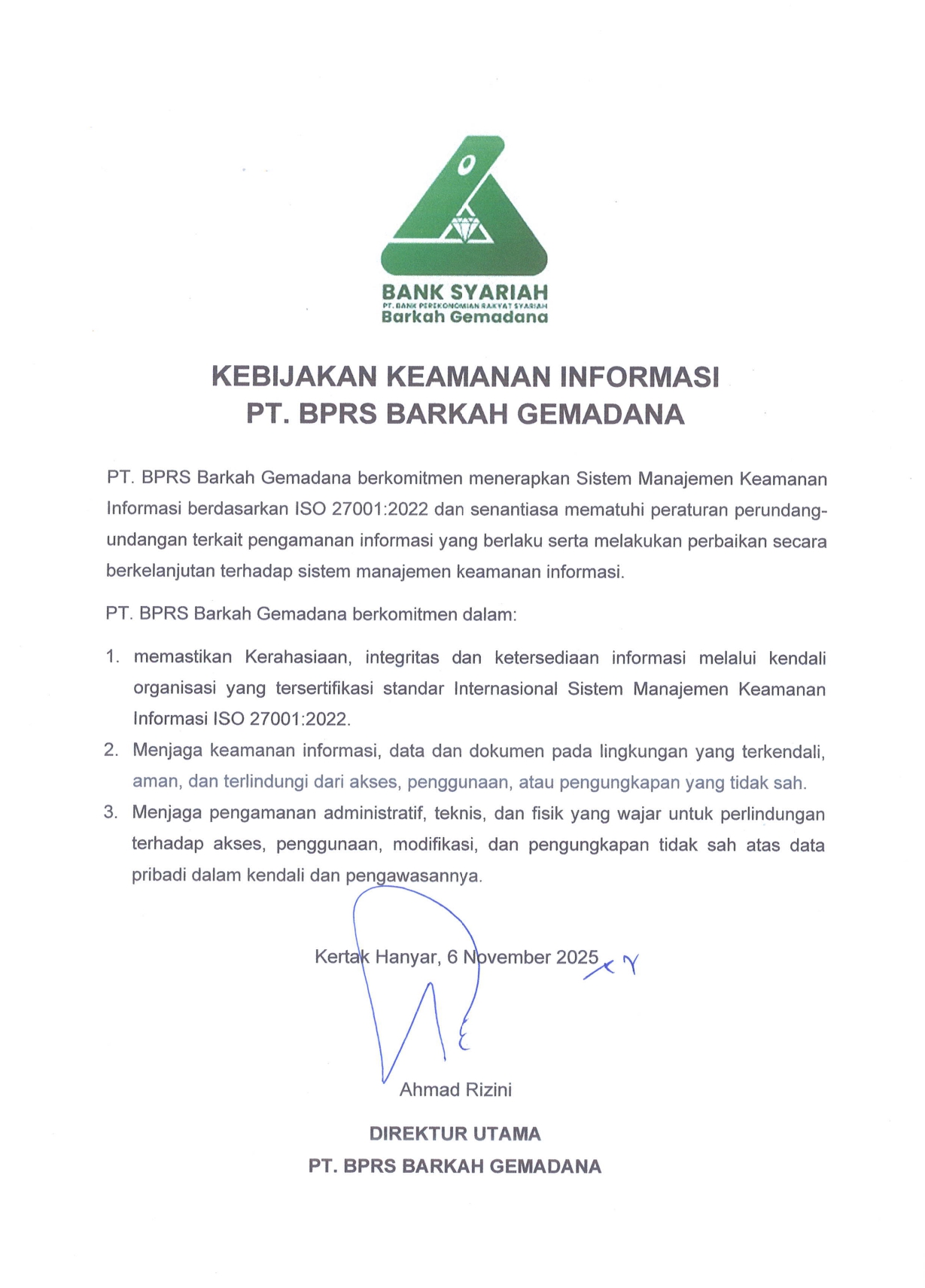Kolom DPS: Media Dakwah dan Kajian Fikih Muamalat
.jpg)
Adab dalam Mengagungkan Syiar Agama
Artikel ditulis Oleh Bapak Dr. H. Sukarni M.Ag (Dewan Pengawas Syariah BPRS Barkah Gemadana)
Beberapa waktu lalu, muncul perbincangan hangat setelah Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Isinya sebenarnya hanya menegaskan kembali aturan tahun 2022 (Nomor 5) mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
Namun, polemik muncul karena sebagian masyarakat kita menjalankan ibadah Ramadan bukan semata berdasarkan tuntunan syariat, tetapi sering kali bercampur dengan kebiasaan lokal yang sudah mendarah daging, seperti tadarus, tarawih, dan takbiran yang disiarkan keras-keras ke luar masjid.
Fenomena ini tidak terlepas dari karakter sosial kita yang kerap menggabungkan ajaran agama dengan tradisi setempat. Dalam sosiologi, hal ini disebut sebagai indigenous knowledge atau pengetahuan asli masyarakat, yang terbentuk demi kelangsungan hidup mereka. Misalnya, di pedesaan Banjar ada larangan pamali atau pemantang yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga harmoni sosial dan alam.
Tradisi seperti ini sering dibalut mitos hasil imajinasi kolektif masyarakat, seperti keyakinan adanya "hantu banyu" di sungai, kuburan keramat, atau pohon angker di pegunungan. Walau dari kacamata Islam, kepercayaan pada hal gaib tanpa dalil syar’i termasuk takhayul yang harus dihindari, secara antropologis mitos tersebut kadang punya efek positif, seperti mencegah kerusakan lingkungan.
Namun, masalah muncul ketika mitos atau tradisi dianggap bagian dari ibadah. Padahal dalam Islam, ibadah adalah perkara tauqifiyyah, yang berarti tidak akan sah kecuali jika ada dalil dari Al-Qur’an atau Sunnah. Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu pernah memperingatkan,
“Ikutilah dan jangan mengada-ada, karena kalian telah dicukupkan” (Riwayat ad-Darimi)
Syariat datang bukan untuk mengadopsi semua tradisi, tetapi untuk meluruskannya sesuai tauhid. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ bersabda,
“Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama/ibadah) kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak” (HR. Bukhari dan Muslim).
Penggunaan pengeras suara di luar masjid saat tarawih, tadarus, atau takbiran sering dianggap “syiar agama”. Sayangnya, banyak yang menyamakan syiar (penanda atau sarana dakwah) dengan siar (penyiaran informasi). Mereka mengukur kualitas keimanan dari seberapa nyaring suara terdengar keluar, seolah-olah makin keras berarti makin islami. Padahal, syiar hanyalah wasilah, bukan tujuan ibadah itu sendiri. Allah ﷻ berfirman:
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ
“Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati” (QS. al-Hajj: 32)
Syiar tidak diukur dari volume pengeras suara, melainkan dari sejauh mana ia menumbuhkan takwa dalam hati dan membawa maslahat serta tidak menimbulkan gangguan.
Dalam fikih, segala wasilah harus tunduk pada kaidah maslahat dan mafsadat. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, bila suatu sarana membawa kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka syariat melarangnya.
Artinya, jika pengeras suara luar membuat sebagian masyarakat terganggu, apalagi di wilayah perkotaan yang padat dan majemuk, maka regulasi untuk membatasi penggunaannya adalah sikap yang bijak. Di desa yang homogen, suara tadarus mungkin jadi hiburan penyejuk hati, tapi di kota bisa menimbulkan ketegangan sosial atau sekadar jadi rutinitas tradisi tanpa ruh ibadah.
Kita perlu jujur. Takbiran keliling kota dengan konvoi kendaraan seringkali lebih terasa sebagai pesta budaya daripada ibadah untuk mengagungkan Allah. Sebagian besar energi habis untuk arak-arakan, bukan dzikir yang khusyu'.
Ulama salaf selalu menekankan bahwa amal yang ikhlas dan sesuai sunnah lebih utama daripada amal yang heboh tapi tidak mengikuti tuntunan. Seperti kata al-Fudhail bin ‘Iyadh:
“Amal yang ikhlas namun tidak sesuai sunnah tidak diterima, begitu juga amal yang sesuai sunnah namun tidak ikhlas.”
Maka, surat edaran ini seharusnya dilihat dengan kepala dingin, bukan emosi. Ramadan adalah momen mendidik diri untuk tenang, bukan adu keras volume. Islam datang membawa rahmat, bukan polusi suara.
Rasulullah ﷺ mengajarkan adab dalam membaca Al-Qur’an, baik didalam shalat ataupun diluar shalat,
“Janganlah sebagian kalian mengganggu yang lain (dengan suara kalian) dalam shalat atau bacaan.” (HR. Malik)
Ini menunjukkan bahwa sekalipun isi bacaannya adalah kalamullah, dan sekalipun itu dilakukan dalam shalat atau tilawah, caranya tetap harus beradab dan mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Di riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda,
لْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ
“Sesungguhnya orang yang shalat itu bermunajat kepada Rabbnya, maka lihatlah kepada siapa yang dimunajatkannya, janganlah kalian menyaringkan bacaan Al-Qur’an di antara satu dengan yang lain."
Jika kita betul-betul ingin menjaga syiar, mulailah dari ketakwaan hati, bukan sekadar gema pengeras suara. Dengan begitu, Ramadan akan benar-benar jadi bulan rahmat, bukan sekadar festival bunyi. Selamat memasuki Ramadan 1445 H, semoga mendapat kemudahan untuk menunaikannya. Aamiin.
Sumber Foto : Canva