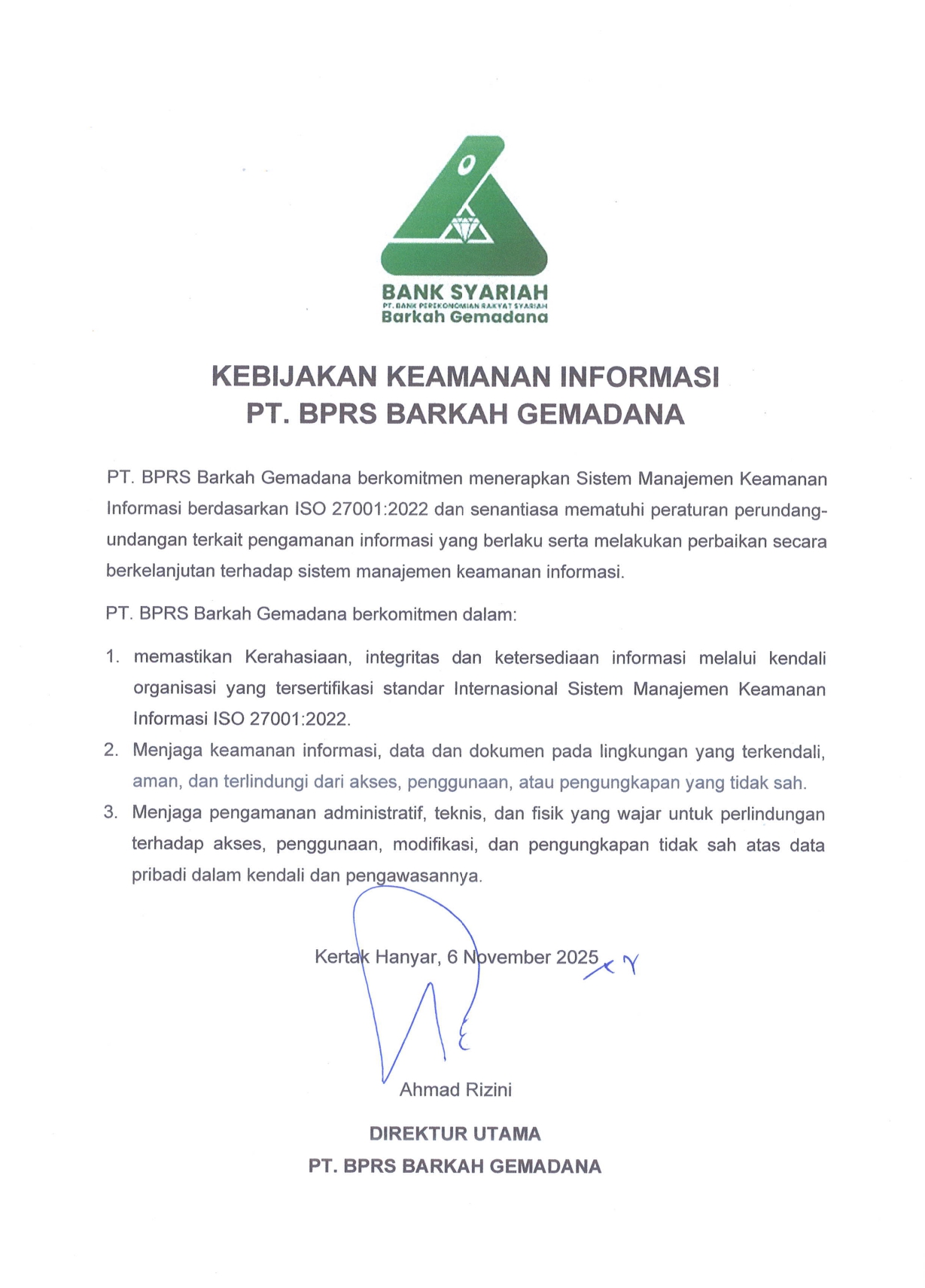Kolom DPS: Media Dakwah dan Kajian Fikih Muamalat

Memahami Hakikat, Dampak, dan Solusi Riba
Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli tanpa dasar yang dibenarkan syariat. Secara bahasa, riba berarti “bertambah” atau “berkembang”. Dalam istilah syariat, riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang atau pertukaran barang ribawi, baik dalam jumlah maupun tempo, yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak secara zalim.
Allah menyebut riba secara tegas dalam Al-Qur’an sebagai sesuatu yang diharamkan, bahkan disejajarkan beratnya dengan dosa perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Firman-Nya,
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” (QS. Al-Baqarah: 278–279)
Riba disebut riba apabila suatu transaksi mengandung unsur tambahan yang disyaratkan, baik berbentuk bunga, margin waktu yang tidak sesuai akad, maupun pertukaran barang sejenis yang tidak sama kadar atau ukurannya. Misalnya, meminjam seratus juta lalu mengembalikan seratus lima juta karena syarat di awal, itu adalah riba nasi’ah. Atau menukar emas lima gram dengan emas tujuh gram secara tidak tunai adalah riba fadhl. Rasulullah ﷺ bersabda,
“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang sama dan sejenis, harus sama kadarnya dan tunai; barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba.” (HR. Muslim).
Jenis riba secara umum ada pada dua bentuk besar. Pertama, riba dalam utang piutang, yang biasanya muncul karena tambahan pembayaran atas pokok utang sebagai kompensasi waktu, seperti bunga bank. Kedua, riba dalam pertukaran barang ribawi, ketika terjadi perbedaan ukuran atau penundaan serah terima pada komoditas yang wajib sama dan tunai. Keduanya merusak keadilan transaksi dan menimbulkan penindasan salah satu pihak.
Riba diharamkan bukan tanpa alasan. Secara agama, riba adalah bentuk kezhaliman yang nyata karena memindahkan kekayaan dari pihak yang lemah kepada yang kuat tanpa usaha riil atau risiko seimbang. Riba merusak kasih sayang sosial, menumbuhkan kerakusan, dan mengikis kepedulian. Allah mengabarkan bahwa harta dari riba akan terhapus keberkahannya, sebagaimana firman-Nya,
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (QS. Al-Baqarah: 276)
Dalam pandangan para ulama salaf, riba adalah penyakit sosial yang membunuh prinsip tolong-menolong. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Ketika riba merajalela di suatu negeri, maka Allah akan menimpakan kegilaan pada mereka.”
Larangan riba bukan hanya ajaran Islam. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 22:25 tertulis,
"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, maka janganlah engkau berlaku seperti penagih hutang; janganlah engkau bebankan bunga kepadanya."
Kitab Ulangan 23:19 juga menyatakan,
"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan."
Bahkan dalam Injil Lukas 6:34–35 disebutkan,
"Dan jikalau kamu meminjamkan kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Bahkan orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan…”
Secara logika ekonomi, riba menciptakan gelembung hutang yang terus membesar tanpa diiringi pertambahan barang atau jasa nyata. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, menegaskan bahwa sistem bunga tinggi dalam jangka panjang mendorong ketimpangan, memperlambat pertumbuhan, dan memicu krisis keuangan. Riba menciptakan distribusi kekayaan yang semakin timpang, karena keuntungan mengalir kepada pemilik modal besar sementara risiko dibebankan pada pihak peminjam.
Data empiris menunjukkan bahwa krisis keuangan global 2008 salah satunya dipicu oleh pembengkakan hutang berbasis bunga yang tak terkendali, memukul masyarakat luas sementara segelintir pihak selamat dengan bailout.
Prinsip syariah hadir sebagai solusi dengan mengganti praktik riba menjadi transaksi yang adil, berbasis kepemilikan risiko dan keuntungan bersama. Dalam syariah, pembiayaan dilakukan melalui akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati di awal), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama modal bersama), dan ijarah (sewa-menyewa).
Semua akad ini menuntut transparansi, kesepakatan di awal, dan menghindari keuntungan tanpa risiko. Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha, prinsip syariah menghubungkan keuntungan dengan realisasi produktivitas, bukan dengan tekanan waktu.
Bagi yang sudah terlanjur terlibat riba dan memiliki tanggungan, sikap yang benar adalah bertaubat dengan segera, menyesali perbuatan, bertekad tidak mengulang, dan mengupayakan pelunasan pokok hutang secepat mungkin tanpa tambahan riba.
Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah: 279, bahwa setelah bertaubat, yang wajib dibayar hanyalah pokok harta. Jika masih terikat kontrak berbunga, upayakan negosiasi dengan kreditur untuk menghapus bunga atau memindahkan pembiayaan ke lembaga syariah. Rasulullah ﷺ bersabda,
“Siapa yang bertaubat dari riba, maka baginya pokok hartanya, dan ia tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” (HR. Abu Dawud).
Sebagian orang masih sering berdalih bahwa bunga adalah harga untuk risiko atau imbal jasa administrasi. Namun ini keliru, karena bunga dibebankan tetap tanpa memperhatikan untung rugi usaha, bahkan saat peminjam rugi, bunga tetap ditagih. Ini berbeda dengan biaya riil atau bagi hasil yang proporsional dengan kinerja usaha. Jika benar bunga hanya imbalan jasa, mestinya nilainya tidak berbasis persentase pokok hutang dan tidak terus berjalan seiring waktu.
Riba adalah bentuk kezaliman yang halus namun mematikan. Ia merusak tatanan ekonomi dan moral masyarakat, mengundang murka Allah, dan menghilangkan keberkahan hidup. Meninggalkannya mungkin berat, apalagi jika sudah terbiasa, tetapi sebagaimana firman Allah,
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (QS. Ath-Thalaq: 2–3).
Jalan keluar itu selalu ada bagi yang mau memutuskan untuk taat. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Aamiin
Sumber foto: Unsplash